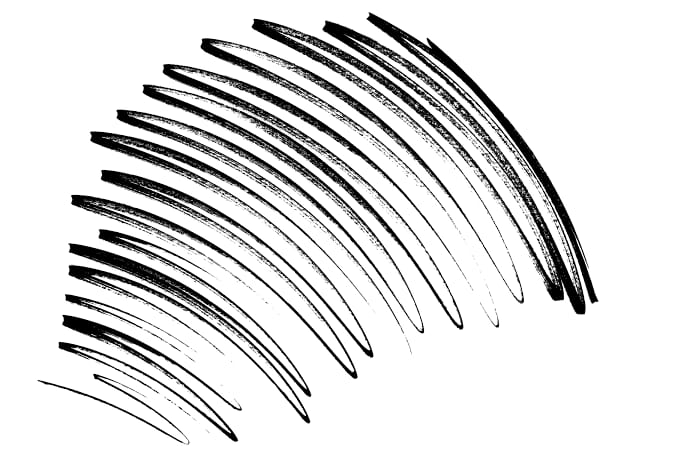“Bu, kenapa kita harus hidup susah?”
Jelang hening sebelum pukul sepuluh, di sebuah gubuk gelap hanya berharap cahaya dari sumbu yang terendam minyak tanah di dalam botol kecil, Ibu Marinah terdiam sejenak kala mendengar pertanyaan Abel. Begitu sulit ia menceritakan nasib badan yang jadi garis kehidupan ke anak semata wayangnya. Pertanyaan itu pula bukan kali pertama ia terima. Namun, ia selalu berusaha menutupi segalanya.
“Nak, kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Di luar sana, masih banyak yang lebih susah dari kita,” jawab sang Ibu sambil mengelus kepala Abel, “Mereka di sana ada yang sama sekali tak punya tempat tinggal. Jadi, sesusah apapun hidup kita, Nak, kita harus bersyukur,” lanjutnya dengan tenang sambil mendekap anaknya agar segera tertidur.
Abel adalah anak yang baik, pintar, dan kritis. Meskipun ia baru duduk di kelas tiga SD, tapi dia tidak seperti kebanyakan anak-anak di zaman sekarang yang hidupnya seperti hanya untuk bermain. Sepulang dari sekolah, Abel selalu membantu sang Ibu mengumpulkan kayu dari patahan ranting. Kayu tersebut kemudian dibakar untuk dijadikan arang lalu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.
Abel tidak pernah mengeluh meski kondisi yang dialaminya tidak seperti kebanyakan teman-temannya di sekolah. Meski begitu, ia tetaplah anak yang polos–yang belum terlalu dalam mengenal sisi kehidupan. Tidak jarang juga ia sering dipandang sebelah mata oleh teman-temannya. Bajunya yang lusuh dan jarang terlihat jajan di sekolah, membuat dirinya sering dianggap orang susah dan tak layak sekolah sebagaimana mestinya.
“Kamu, Bel, sudahlah hidup susah, di dalam hutan lagi, baju tak pernah rapi, pergi sekolah jalan kaki, terus maennya mau sama kami pula, sadar woi,” cetus Abdul saat ketika Abel ingin bergabung bersama beberapa teman-temannya di sekolah yang sedang main Goli (kelereng).
“Hahaha, dia Dul, mana punya Goli. Ujung-ujungnya Nunggu belas kasihan dari kita juga,” Ijuk menyambung celoteh Abdul sambil tertawa hina.
Abel tersenyum berharap, sebelum akhirnya didorong Malik hingga terjatuh ke tanah, “Woy, ngacaklah. Uang jajan aja tak punya mau main goli,” ucap Malik sambil mendorong Abel.
Ketiga sekawan tersebut memang selalu menjadi provokator agar si Abel dijauhkan dari teman-teman yang lainnya. Sering kali mereka menghina Abel dengan perkataan-perkataan tak pantas. Apalagi mereka masih terbilang anak-anak yang masih belajar. Sungguh sangat tidak mencerminkan bahwa adanya pendidikan di usia dini.
“Kalian kenapa benci sekali sama Abel?” Tanya Abel yang baru saja terjatuh dan terduduk di tanah.
“Bel, kamu tahu tak, kamu itu miskin. Kamu cuma pintar belajar tapi urusan lainnya, kamu tak bisa apa-apa,” celetuk Zilla salah satu anak perempuan yang menjadi teman sekelas Abel dan Abdul juga lainnya.
“Betul tuh, Zil. Aku setuju. Kamu itu Bel, boleh jadi teman kita kalau pas ujian dan ulangan aja. Selebihnya, tolong dech, jangan berharap, ya,” kata Abdul sambil tertawa.
Di sekolah, meskipun ia berprestasi sebagai juara kelas sejak dini, tapi keberadaannya tak pernah benar-benar diakui. Ia hanya dijadikan tumbal anak-anak untuk mendapatkan jawaban setiap kali mengerjakan latihan, ulangan harian, bahkan ujian akhir semester. Mirisnya lagi ketika ia menolak memberi jawaban, akan selalu ada pukulan mendarat di pipi dan dorongan tak lazim hingga terjatuh.
Abdul dan kawan-kawan juga sering mengancam Abel apabila perbuatan mereka sampai ke telinga Guru. Suatu hari, saat Abel dituduh memberi jawaban yang salah, sepulang dari sekolah ia dihajar habis-habisan hingga baju sekolahnya koyak.
“Bel, berani-beraninya kau ya kasih jawaban yang salah ke kami,” cetus Ijuk ke Abel saat pulang sekolah. Rumah Abel yang terletak di dalam belantara pohon Karet, membuat segala rencana Abdul dan kawan-kawan berjalan mulus. Sebab perjalanan dari sekolah menuju rumahnya sangat sepi.
“Kami semua harus remedial. Jawaban yang kemarin kau berikan tak ada yang betul satu pun. Maksud kau apa? Sengaja mau buat nilai kami hancur?” Suara Abdul sangat tinggi seolah ingin menerkam Abel yang kala itu masih kebingungan.
Kala itu mereka sudah kelas lima. Peristiwa itu terjadi ketika ujian akhir semester ganjil. Abel sudah memberikan jawaban yang benar, tapi karena Abdul adalah orang yang tidak suka membaca, akhirnya jawaban yang diberikan ditulisnya di kolom jawaban yang lain. Alhasil, jawaban itu salah semua dan berimbas juga ke kawan-kawan yang lainnya.
Baku hantam tanpa perlawanan pun terjadi. Abel bersandar di pohon karet sambil menangis. Selain itu, Zilla dan beberpa teman perempuan yang lain menyirami Abel dengan air Ojol (hasil getah pohon karet) yang sangat bau sekali.
“Jangan coba-coba kau mengadu kejadian ini ke guru. Kalau kau berani melakukannya, akan ada yang lebih parah dari ini,” ancam Abdul sebelum akhirnya mereka semua pergi meninggalkan Abel sendirian.
*
“Ayu, Kamu tahu, setelah kejadian di bawah pohon karet itu, aku pulang, belum hilang sedihku karena ulah teman-temanku, aku harus melihat ibu terbaring dan tak bernyawa,” Abel tertunduk melanjutkan cerita masa kecilnya ke Ayu, “ibu meninggal karena serangan jantung. Sejak itu aku menjadi yatim piatu, dan aku tak pernah tahu kenapa kami harus hidup susah. Ibu tak pernah menjawab pertanyaanku,” sambung Abel.
“Abel, kenapa kamu tak pernah menceritakan semua itu selama ini?” Spontan ayu bertanya dalam terkejutnya ia atas malangnya nasib Abel di masa kecil.
“Aku tak mau hidup dipenuhi belas kasihan hanya karena aku yatim piatu dan hidup susah,” jawab Abel tegar tanpa memperlihatkan kesedihan yang tak pernah habis dirasakan.
“Tapi kamu kan masih bisa kuliah, dan sekarang kamu justru bisa mempekerjakan orang-orang yang membutuhkankan. Lantas kenapa kamu merahasiakan semua ke orang, termasuk aku,” cetus Ayu yang tak percaya bahwa ternyata selama ini Abel sanggup menyimpan rapat-rapat pengalaman pahit hidupnya.
Ayu adalah sahabat terbaik Abel. Mereka dipertemukan saat pertama kali keduanya mengemban status mahasiswa di sebuah Universitas ternama di Indonesia. Selama kuliah, mereka sangat akrab dari proses ospek hingga akhirnya wisuda bersama. Keduanya juga mahasiswa berprestasi; sama-sama mendapatkan beasiswa yang besar hingga selesai. Hal Itu juga menjadi alasan mengapa akhirnya ia bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi meski hanya hidup sebatang kara sejak SD kelas 5 dan bertahan hidup hanya menjadi seorang penjual arang.
“Dulu, aku tak bisa apa-apa, Yu. Aku cuman dibekali pengalaman kerja sebagai pemungut kayu yang kemudian kayunya dijadikan arang,” Abel tersenyum lepas memandang Ayu, “Tapi aku berusaha bertahan hidup, dan terus belajar. Sampai akhirnya aku lulus SMA dan dapat beasiswa,” lanjutnya sambil menatap langit setengah sore di depan cafe miliknya.
Mendengar cerita dari Abel, Ayu sangat terharu. Desir kagum pun tak bisa dipungkiri. Selama ini ternyata ia berteman dengan sosok yang tak kenal menyerah. Lelaki pejuang yang tak mengeluh meski hidupnya dirundung pilu. Kesendirian tak membuat jalan hidupnya terhenti.
“Selama itu kamu tak memiliki teman? Terus, aku masih belum paham bagaimana kamu bisa lalui itu semua?” Tanya Ayu penuh makna di balik haru dan kekagumannya dengan Abel.
“Teman-teman sekolahku tak pernah peduli siapa aku. Mereka hanya butuh isi kepalaku saja. Setelah apa yang mereka ingin didapat, aku hanya menjadi bahan gunjingan,” cerita Abel dengan tawa tipisnya, “Aku juga tak tahu kenapa aku bisa lalui semuanya sampai sekarang. Padahal, jujur, itu berat sekali rasanya. Apalagi ketika aku melihat orang lain yang bahagia karena keluarganya masih utuh, sedangkan aku di rumah hanya bisa ngomong lewat gambar ibu dan ayah,” sambungnya.
Kepergian ibunya kala itu membuat dirinya harus menerima bahwa tiada teman bicara di rumah rasanya hampa dan gulana. Ia hanya bisa memandang potret usang yang kusam sebagai pelipur sepi nan lara.
“Ayah kamu meninggal karena apa?” Tanya Ayu penasaran.
Sebelum menjawab pertanyaan Ayu, Abel sempat terdiam dan menatap langit. Hatinya berharap bisa melihat lukisan wajah Sang Ayah di latar biru yang luas berhias awan. Rindu yang amat dalam ia rasakan seperti ingin menguras air matanya. Namun, ia mencoba baik dan menarik napasnya perlahan, “Ayah pergi karena jatuh dari pohon kelapa saat ia ingin memetik kelapa muda untuk ibu yang sedang mengandungku. Kata ibu, saat Ayah jatuh kepalanya mendarat lebih dulu,” Abel mengulur napasnya perlahan, “sampai hari ini, aku tak pernah bertemu dengan ayah,” sambungnya.
Sejak lahir, Abel sudah harus menangis tegar tanpa mendengar suara dan melihat keberadaan Sang Ayah tercinta. Belum cukup usianya memasuki remaja, ia juga harus kehilangan Ibunya karena serangan jantung. Ia melanjutkan hidupnya sendirian penuh kerinduan akan belaian kasih sayang orang tua. Entah mengapa, saudara-saudaranya tidak ada yang peduli pada dirinya. Ia dibiarkan hidup susah sendiri di gubuk tak bercahaya saat malam hari. Namun belasan tahun Abel lalui dengan sabar, perjuangan, dan terus belajar sehingga ia kini menjadi seorang sarjana dan pengusaha.
“Aku bangga punya teman setangguh kamu. Kamu luar biasa. Kamu berhasil menutup rapat pilunya hidup dengan prestasi, usaha, dan mandiri,” ujar Ayu sambil tersenyum haru sebab terhanyut akan cerita Abel yang pilu.
“Aku juga bangga punya teman sepertimu. Kamu adalah orang pertama yang mau jadi teman yang tulus. Bukan karena isi kepalaku. Sejak mengenalmu, aku merasa dunia tak seburuk yang aku kira,” ungkap Abel.
“Oh ya, aku juga sangat kagum samamu yang tak memiliki sikap dendam ke teman-teman dan saudaramu. Padahal aku tahu hatimu sangat sakit kan. Aku yang hanya mendengar saja, bisa merasakan betapa sakitnya. Apalagi kamu, Bel?”
Abel pun tersenyum mendengar ucap Ayu, “saat terakhir kali aku bertanya sama ibu, kenapa harus hidup susah, ibu hanya menjawab, jika kita tidak bisa hidup dengan kemewahan, hiduplah dengan penuh kebaikan. Ibu berpesan, dengan kebaikan kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin tidak sekarang atau dalam waktu yang cepat, tapi Tuhan tak pernah menutup mata atas kebaikan apa saja yang kita lakukan,” ungkap Abel sebelum akhirnya mereka mengakhiri pertemuan sore.
Benar memang, kadang kita perlu belajar banyak hal dari kehilangan dan kebaikan. Dendam bukanlah jalan yang tepat untuk membuktikan yang selama ini menjadi gunjingan. Tetaplah berbuat baik, sebab dengan kebaikan kita bisa hidup lebih dari kenyamanan.